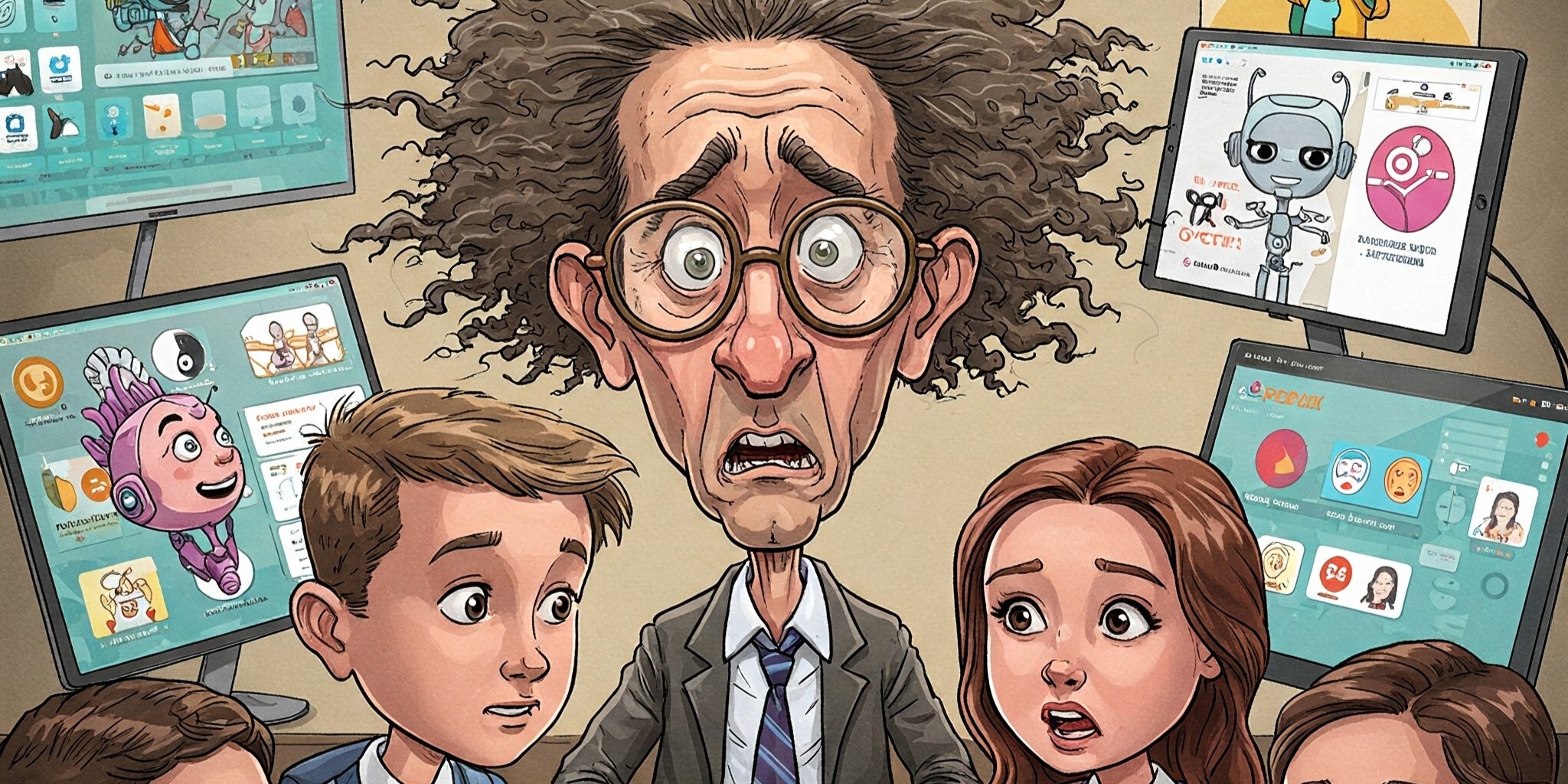Mewarta.com. Opini – Bayangkan, Kelas masa depan di mana siswa tak hanya belajar dari guru, tapi juga didampingi asisten virtual yang serba tahu dan tak pernah lelah menjawab. AI membuka gerbang ilusi itu lebar-lebar, menyusup ke setiap sudut pendidikan kita, dari kota metropolitan hingga pelosok desa, dari sekolah elite hingga madrasah sederhana, bahkan merasuki dunia daring yang semakin tak terkendali. Tapi jangan tertipu! Di balik janji kemudahan, tersimpan dualitas yang mengancam inti dari pendidikan itu sendiri.
AI hadir dalam rupa aplikasi canggih, katanya membantu guru mengelola kelas, menganalisis perkembangan siswa, bahkan menyediakan materi ajar yang ‘dipersonalisasi’. ChatGPT, Khan Academy, Asisten Google – nama-nama yang kini akrab di telinga siswa dan guru. Nadiem Makarim bahkan pernah berujar, AI adalah ‘peluang besar’ untuk pembelajaran yang lebih inklusif, katalisator transformasi, bukan ancaman. Tapi benarkah demikian? Apakah kita terlalu naif untuk menelan mentah-mentah optimisme ini?
AI memang menjanjikan keringanan beban administratif bagi guru, dan menjadi ‘teman belajar’ yang sabar bagi siswa. Tapi apakah esensi pendidikan hanya sebatas efisiensi dan ketersediaan informasi 24/7? Bukankah ada dimensi afektif dan sosial yang justru terancam punah jika kita terlalu mengandalkan mesin? Prof. Zulkifli dengan tegas mengingatkan kita untuk berhati-hati. Efisiensi memang penting, tapi jangan sampai kita mengorbankan jiwa dari proses belajar itu sendiri.
AI mungkin bisa menjawab segala pertanyaan, tapi ia takkan pernah bisa merasakan kegelisahan seorang siswa yang tertinggal. Ia takkan mampu menangkap bahasa tubuh seorang anak yang butuh dukungan lebih. Ruang inilah yang takkan pernah bisa digantikan oleh algoritma secanggih apa pun.
Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah jurang ketimpangan yang semakin menganga. Tidak semua sekolah punya akses ke infrastruktur digital. Tidak semua guru siap menghadapi revolusi teknologi ini. Jika kita gegabah, AI justru akan memperlebar jurang pendidikan antara si kaya dan si miskin, antara kota dan desa. UNESCO pun telah memperingatkan: AI harus berpusat pada manusia, mendukung keadilan, bukan menggantikannya. Tapi apakah kita benar-benar mendengarkan?
Alih-alih menjadi pengganti, guru dan AI seharusnya bisa berkolaborasi. Guru tetaplah nahkoda nilai, pembimbing karakter, pemberi makna. AI hanyalah alat bantu untuk eksplorasi dan personalisasi. Tapi bisakah kita yakin bahwa kolaborasi ini tidak akan berujung pada ketergantungan yang membahayakan? Bisakah kita menjamin bahwa guru tidak akan tergerus perannya menjadi sekadar operator teknologi?
Yuval Noah Harari dengan nada serius mengingatkan kita: ketika AI bisa menulis lebih baik dari manusia, siapa yang mengontrolnya dan untuk tujuan apa? Peringatan ini seharusnya membuat kita merinding. Di balik kecanggihan teknologi, tersembunyi isu etika, kekuasaan, dan tanggung jawab yang tak boleh kita abaikan sedikit pun.
Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. AI bisa membuat pembelajaran lebih efisien, tapi tidak otomatis membuatnya lebih manusiawi. Di sinilah letak tanggung jawab kita sebagai pendidik: menjaga ruh dalam proses belajar. Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tapi juga pembentukan akhlak dan adab. Rasulullah ﷺ adalah teladan utama, bukan karena teknologi canggih, tapi karena keteladanan dan kelembutan hatinya.
Kita harus memanfaatkan AI untuk memperkuat nilai memanusiakan proses belajar. Jika kita gagal, kita sedang menuju masa depan pendidikan yang mungkin cerdas secara algoritma, tapi kering kerontang dari kebijaksanaan dan empati.
Kehadiran AI di ruang kelas bisa menjadi kawan, jika kita membangun relasi yang bijak. Tapi ia juga bisa menjadi ancaman nyata jika kita menutup mata dari dampaknya yang kompleks. Sebagaimana kata Prof. Fasli Jalal: pendidikan itu membentuk manusia, bukan hanya mencerdaskan. Teknologi hanyalah alat bantu, dan manusia tetaplah intinya.
Maka, kehadiran AI bukanlah untuk menggantikan guru, tapi untuk menguatkan perannya. Bukan untuk mengasingkan siswa, tapi mendekatkan mereka pada proses belajar yang bermakna. Karena sejatinya, pendidikan adalah tentang hati, bukan hanya otak. Dan AI, secerdas apa pun, belum punya hati.
(Muh Anwar. HM)